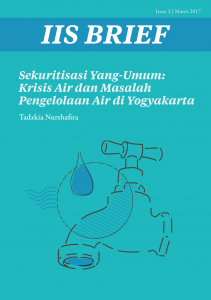Issue 06 | September 2017 (https://simpan.ugm.ac.id/s/MazMlUHxQDByFOr#pdfviewer)
Kebangkitan populisme sayap kanan di negara-negara demokratis terasa menggelisahkan bagi pluralis-demokrat. Berbagai elemen pendukung populisme sayap kanan dianggap sebagai kelompok yang tidak normal. Begitu pun di Indonesia, kelompok yang melabeli diri Islamis dianggap sebagai musuh demokrasi. Di sisi lain, kelompok pendukung status quo sebagai pemilik narasi hegemonik selalu berlindung di balik ide bahwa Pancasila, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan HAM sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh ditentang, baik pada dirinya dan final. Dengan begitu, definisi politik menyempit karena ia dianggap sebagai masalah moralitas dan etika semata. Dimensi politik yang esensial—bahwa politik adalah soal pertentangan terus-menerus di antara berbagai kepentingan berbeda—justru disisihkan dari perbincangan tentangnya. Populisme sayap kanan yang kini bangkit adalah konsekuensi dari penyempitan makna politik tersebut.
Populisme sayap kanan mulai mendapat perhatian sejak kebangkitan Partai Front Nasional dalam Pemilu Prancis tahun 2002. Raihan suara sebesar 17.8% membuka kesempatan bagi Front Nasional untuk mengajukan kandidat presiden pertama sepanjang sejarah partai, yakni Marie Le Pen (The Guardian, 2002). Pada Pemilu Prancis 2017, partai yang sama meraih 33.9% suara dan kembali mengusung Le Pen sebagai kandidat. Seiring dengan kebangkitan Front Nasional di tahun 2002, partai-partai sayap kanan di Eropa perlahan berhasil berhadapan dengan partai yang secara tradisional dominan. Partai-partai ini seringkali bangkit dalam konteks pemilu yang penuh dengan sentimen anti-pengungsi, anti-pluralisme, maupun anti-kemapanan.
Negara-negara di Eropa tidaklah sendiri. Populisme sayap kanan juga mendapat momentum di Amerika Serikat (AS)—negara yang mengklaim sebagai wajah demokrasi—dengan terpilihnya Donald Trump yang rasis. Asia juga tidak luput dari bangkitnya populisme sayap-kanan. India, Filipina, Jepang, dan dalam derajat tertentu—apabila kita merujuk pada Aksi Bela Islam 411 dan 212—Indonesia memiliki pengalaman yang sama beberapa tahun belakangan. Meski masing-masing memiliki konteks yang berbeda, populisme sebagai mode artikulasi aspirasi sosial, politik atau ideologi apapun yang menciptakan polarisasi antara mereka yang melihat dirinya sebagai ‘rakyat’ (people) melawan rezim yang mapan (establishment) tetap nampak dalam kasus-kasus tersebut. Mengapa populisme sayap kanan bangkit dan mendapat dukungan besar saat ini?
Dalam sudut pandang pemikir pasca-strukturalis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, populisme sayap kanan muncul karena wacana yang dominan saat ini menghilangkan dimensi yang-politis dari politik, sehingga tidak ada ruang alternatif bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya selain melalui diskursus sayap kanan yang dianggap paling mampu mengakomodasi aspirasi mereka. Dimensi politis hilang ketika arena publik dihegemoni oleh berbagai wacana yang seolah diperlakukan sebagai produk konsensus. Konsekuensinya, wacana hegemonik tersebut tidak memperoleh tantangan apapun.
Demokrasi liberal sebagai wacana dominan saat ini tidak memiliki kapasitas untuk memahami karakter dasar politik yang sebagai pertentangan terus-menerus di antara klaim-klaim politik yang berbeda (Mouffe, 1993). Kelompok yang bermacam-macam di dalam suatu komunitas politik memproduksi wacana yang beragam, saling bertentangan, juga konfliktual. Justru pertentangan dan pluralitas inilah yang membuat politik menjadi politis (Mouffe, 2005).
Sejak narasi konfliktual mengenai komunisme dan liberalisme berakhir pada kejatuhan Uni Soviet tahun 1989, neoliberalisme dan globalisasi yang menjadi narasi dominan saat ini membuat pertentangan wacana menjadi kabur. Keduanya menghilangkan nuansa politis banyak isu publik dan membuatnya nampak seperti keharusan moral semata, misalnya HAM, toleransi, dan good and transparent governance. Dalam bahasa populer, politik menjadi ‘business as usual’; entah ia melanggengkan ketimpangan karena kapitalisme, atau mendekati narasi-narasi yang menantang status quo dengan cara yang sangat legalistik.
Dalam politik negara-negara Barat, baik partai sosial-demokrat, partai konservatif, maupun partai liberal sama-sama mendukung kapitalisme dan tidak menghadirkan celah bagi alternatif lain untuk warga. Keadaan sama terjadi pula di beberapa negara Asia seperti Indonesia, India, atau Filipina dengan partai yang tidak memiliki ideologi, keberpihakan maupun kebijakan spesifik. Mereka sekadar menjadi partai catch-all[1]. Masyarakat dituntut untuk melihat kontes politik praktis sekadar sebagai kompetisi moral dan etika. Kemunculan populisme sayap kanan merupakan konsekuensi dari depolitisasi ini. Massa yang selama ini tidak pernah mendapat akses untuk memunculkan narasi politis ke ruang publik kini mendapatkan sebuah payung, dan saat ini, payung tersebut merupakan identitas yang sangat primordial seperti ras, agama, dan etnis (Mouffe, 2005).
Populisme bekerja dengan membentuk narasi yang memisahkan masyarakat menjadi ‘kami’ (us) dan ‘mereka’ (them); popular sovereignty dan establishment; radikal dan demokrat; nasionalis dan moderat. Keduanya saling mengeksklusi satu sama lain. Sebenarnya di dalam kedua narasi ini tetap terdapat keberagaman opini, wacana, dan klaim. Tetapi keberagaman ini dapat menemukan koherensi ketika ada payung yang bisa merepresentasikan klaim dan wacana tersebut (Laclau, 2005; Mouffe, 1993). Gagasan mengenai popular sovereignty muncul karena demokrasi liberal di negara-negara demokratis justru tidak menyisakan kesempatan yang berarti bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam keputusan penting. Padahal legitimasi demokrasi itu secara prinsip berasal dari rakyat. Defisit demokrasi ini menjadi celah bagi kelompok sayap kanan untuk mengklaim diri mewakili rakyat.Dalam banyak fenomena populisme akhir-akhir ini, label yang paling terlihat dalam ‘the people’ adalah fundamentalisme agama dan ras. Kedua hal tersebut menjadi hantu besar bagi demokrasi karena karakternya yang eksklusif. Agama familiar diperlakukan sebagai alat untuk mencapai posisi politik yang menguntungkan bagi beberapa orang. Tetapi bagi banyak orang lain, identitas mereka sebagai pemeluk agama A, B, C yang sakral sudah cukup untuk mewakili perlawanan atas keadaan sosial-ekonomi mereka terhadap status quo.
Salah satu contoh kasus adalah Bharatiya Janata Party (BJP) di India yang mengusung Narendra Modi sebagai Perdana Menteri. BJP merupakan partai yang berideologikan Hindutva dengan visi membuat India sepenuhnya milik komunitas Hindu. Modi mendapatkan kedudukannya saat ini karena kooperasi lintaskasta di India yang merasa tertekan dengan berkembangnya penguasa dan kelas menengah Muslim. Sebelumnya, India di era Manmohan Singh mempertahankan sekularisme untuk mencegah perpecahan masyarakat dan memfokuskan negara pada pembangunan dan liberalisasi ekonomi yang cepat. Meski mampu mengantar India tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, namun pembangunan dan proyek ekonomi di era Singh cenderung mengabaikan konstituen besar Hindu (40%) yang sedang bangkit, yaitu kelompok other backward caste (OBC) yang berasal dari kasta ksatria dan waisya. OBC sendiri tidak pernah menerima aksi afirmatif. Kelompok ini berusaha mempertahankan posisinya di tengah persaingan urban dengan kelompok Muslim yang kelas menengahnya pun sedang berkembang. Modi hadir dengan basis sosial dari OBC yang disebutnya sebagai ‘neo-middle class’—memberikan tanda bahwa kelompok ini menentukan proyek ekonomi Modi (Sridharan & Varshney, 2001). Dalam kasus ini, BJP yang secara tradisional berideologi Hindutva menyediakan kendaraan bagi kelompok lintaskasta yang tertekan untuk menyuarakan aspirasinya. Sekularisme yang selama ini dianggap konsensus pun dipertanyakan dalam keadaan demikian.
Begitu pula yang terjadi di AS dan Eropa. Privilese ekonomi kelas menengah kulit putih terancam hilang karena mereka harus bersaing dengan imigran dari ras lain seperti orang kulit hitam dan Muslim. Ketiadaan jaminan sosial di AS, ekonomi yang sedang lesu di Eropa dan AS, serta penguasa yang tidak berpihak pada kelas pekerja kulit putih turut memengaruhi pilihan mereka untuk mendukung gerakan sayap-kanan maupun para pemimpin berideologi nasionalis ekstrim karena pemimpin ini mengartikulasikannya dalam kampanye mereka (The Guardian, 2016). Alih-alih, elit moderat menyatakan afirmasi bagi LGBT, perubahan iklim, dan memberi kuota bagi pengungsi—hal-hal yang bagi kelas pekerja kulit putih tidak mewakili kepentingan mereka.
Gambaran serupa dapat disaksikan di negeri kita sendiri. Kelompok Islam politik semakin kuat karena mereka memiliki narasi yang menghadapkan Islam pada sebuah keadaan yang merugikan dan memarjinalkan kelompok Muslim. Aksi 411 dan 212 yang memprotes Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat dukungan dari banyak kaum Muslim Jakarta yang ruang hidupnya dan opininya dihilangkan oleh penguasa demi kepentingan kelas menengah. Penggusuran rumah tanpa komunikasi yang baik demi sebuah lahan bermain kelas menengah, kondisi kerja yang tidak ramah bagi kaum miskin kota, ruang publik yang terus dieliminasi digantikan pusat perbelanjaan yang menawarkan ruang publik semu, lingkungan hidup yang dicemari oleh reklamasi, pabrik-pabrik besar, juga proyek betonisasi di Jakarta memicu kekecewaan terhadap Ahok atau elit politik yang berkuasa.
Betapapun intensnya kampanye mengenai Pancasila, persatuan, dan toleransi, tetap saja tidak dapat menautkan visi mereka dengan penderitaan kaum miskin urban. Kelompok Islam radikal-lah yang dapat memayungi penderitaan tersebut; mereka yang memiliki sebuah konsepsi berbeda mengenai seperti apa seharusnya toleransi, demokrasi, atau Pancasila—konsepsi yang selama ini dianggap terberi, tidak terelak, tidak tertandingi. Populisme sayap kanan karenanya merupakan disrupsi terhadap politik sebagai business as usual serta mengeskpos natur politik yang selalu dipenuhi pertentangan.
Kebangkitan populisme sayap kanan sebagai konsekuensi dari depolitisasi tidak membuat demokrasi kehilangan relevansinya. Selama arena politik tidak ditutup, maka kontestasi di antara berbagai narasi merupakan tanda bahwa demokrasi itu masih ada. Pada akhirnya populisme sayap kanan pun lebih banyak mengikuti prosedur demokrasi yang berlaku dalam menyampaikan aspirasi politiknya, meskipun aksi kekerasan masih terjadi, seperti aksi supremasis kulit putih yang menewaskan seorang warga di Charloteville, pemboikotan acara keagamaan, maupun aksi vigilantisme.
Setiap pemain dalam arena politik memiliki segala kesempatan untuk dapat berpartisipasi dan menciptakan narasi hegemonik. Mereka yang mengklaim dirinya liberal atau moderat perlu mempertimbangkan untuk bersikap terbuka tidak hanya pada keberagaman primordial, tetapi juga keberagaman narasi dan ide yang hadir dalam ruang publik, serta melihat konteks yang lebih besar di balik teriakan-teriakan yang terdengar rasis, xenophobik, atau supremasis. Dengan memahami ide yang berseberangan, maka kelompok moderat sebenarnya mempertahankan dimensi pluralisme demokrasi serta mengevaluasi cara mereka merepresentasikan suara masyarakat.
—
Naomi Resti Anditya
Asisten Riset Institute of International Studies,
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada
naonugroho@gmail.com
—
Catatan Kaki
[1] Partai ‘catch-all’ adalah istilah untuk partai politik yang tidak memiliki ideologi spesifik. Partai ini berupaya untuk menarik suara dari orang-orang dengan pandangan yang beragam dalam jumlah besar.
—
Referensi
- Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London: Verso.
- Mouffe, C. (1993). The Return of The Political. London: Verso.
- Mouffe, C. (2005). The ‘End of Politics’ and the Challenge of Right-wing Populism. Dalam F. Panizza, Populism and the Mirror of Democracy 1. London: Verso.
- New York Times. (2016, 4 Desember). Europe’s Rising Far Right: A Guide to the Most Prominent Parties. Dipetik tanggal 31 Agustus 2017, dari New York Times:https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/europe-far-right-political-parties-listy.html?mcubz=1.
- Sridharan, E., & Varshney, A. (2001). Toward Moderate Pluralism: Political Parties in India. Dalam L. Diamond, & R. Gunther, Political Parties and Democracy. Maryland: John Hopkins University Press.
- The Guardian. (2002, 22 April). Le Pen vote shocks France. Dipetik tanggal 31 Agustus 2017, dari The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2002/apr/22/thefarright.france.
- The Guardian. (2016, 9 November). Why did people vote for Donald Trump? Voters explain. Dipetik tanggal 18 September 2017, dari The Guardian: https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/why-did-people-vote-for-donald-trump-us-voters-explain.
—
Setiap tulisan yang dimuat dalam IIS Brief merupakan pendapat personal penulis dan tidak merepresentasikan posisi Institute of International Studies.
From <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/iis_brief/issue06-2017/>
21 September 2017 By Publikasi IIS