[RECAP] Beyond The Great Wall #9 : Cina dan Problematika di Era New Normal
Pada Sabtu (11/7) lalu, Institute of International Studies (IIS) UGM kembali mengadakan forum diskusi dwibulanan Beyond the Great Wall (BTGW) secara daring. BTGW edisi kesembilan menghadirkan Julian Lilihata, MA, alumnus Tsinghua University dan Arrizal Anugerah Jaknanihan, mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. BTGW edisi kali ini bertajuk “Cina: Problematika di Era New Normal” untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi Cina di era new normal sembari terus berusaha menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga usai.
Forum diskusi diawali dengan pemaparan oleh Julian mengenai “Gelombang Kedua Virus Corona di Beijing”. Pada gelombang pertama penyebaran virus COVID-19 di Wuhan, terdapat kebimbangan dengan adanya kesimpangsiuran pemberitaan mengenai perkembangan awal kasus infeksi. Menurut South China Morning Post, kasus pertama terdeteksi pada 17 November 2019, sedangkan menurut Wall Street Journal, kasus pertama terdeteksi pada 10 Desember 2019. Pada masa awal penyebaran virus, terdapat beberapa dokter yang berusaha memperingatkan rekan sejawat mereka akan adanya kasus infeksi mirip SARS. Namun, Biro Keamanan Publik Wuhan memanggil dan melakukan represi terhadap delapan dokter tersebut dengan meminta mereka menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan aktivitas ilegal yang mengganggu keamanan publik. Penandatanganan ini disiarkan secara publik lewat Xinwen Lianbo.
Penanganan yang terbilang serius baru dijalankan di awal 2020. Pada 1 Januari 2020, Pasar Makanan Laut Huanan—tempat kasus-kasus pertama COVID-19 terdeteksi—ditutup. Dua minggu setelahnya, pengukuran suhu dilakukan di berbagai tempat umum. Penduduk yang demam langsung segera dirujuk ke klinik demam. Dua kasus COVID-19 di Beijing secara resmi terdeteksi pada 19 Januari 2020. Lima hari setelah kasus terdeteksi, telah banyak aksi pencegahan yang dilakukan seperti libur kerja, penyediaan masker dan hand sanitizers, pemeriksaan suhu di banyak titik, disinfeksi bangunan, penanganan pasien dengan gejala demam secara terpusat di 89 rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas klinik demam, penghentian kegiatan ibadah, dan penutupan layanan transportasi jarak jauh. Faktor yang berkontribusi membuat penyebaran virus ini semakin meluas adalah kesibukan penduduk pada satu minggu menjelang libur tahun baru Cina yang berlangsung pada pada 24 Januari-2 Februari. Selama periode tersebut, arus transportasi masih berjalan normal, seperti sebelum lockdown diberlakukan dan banyak orang telah mengambil cuti dari seminggu sebelumnya, sehingga menimbulkan indikasi pergerakan penduduk yang telah terjangkit di hari-hari sebelum lockdown diberlakukan.
Dengan adanya arus balik libur tahun baru Cina, periode puncak pertama infeksi wabah di Beijing terjadi pada 5 Februari dengan tambahan 114 kasus. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah mengusahakan berbagai cara untuk mencegah penyebaran. Demi memberikan informasi secara tepat dan akurat untuk merespon wabah, pemerintah meluncurkan aplikasi Beijing Health Kit Apps. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai media komunikasi dari pemerintah ke masyarakat terkait kebijakan selama pandemi sekaligus sebagai kartu identitas jika bepergian ke ruang publik. Selain itu, pembelian obat demam di apotek mewajibkan pelaporan KTP agar tercatat. Biro Keamanan Sosial Beijing pun memberikan perlindungan keluarga berpenghasilan ganda. Sebagai hasil dari respon yang cepat ini, terjadi penurunan kurva yang signifikan antara dua minggu pertama dengan dua minggu terakhir di bulan Februari.
Akibat pandemi, terdapat berbagai perubahan dan upaya adaptasi yang dilakukan, seperti munculnya revolusi tata cara makan. Adaptasi juga dilakukan dengan menghimbau warga asing untuk tidak kembali ke Beijing sebab banyak kasus COVID-19 yang merupakan kasus “impor”, yakni tercatat pada orang-orang yang tiba di Beijing dari negara lain. Pemerintah bahkan menghentikan penerbangan langsung ke Beijing dan mengalihkannya ke beberapa kota sekitar Beijing dengan angka infeksi COVID-19 yang lebih rendah. Tiga hari setelah kasus COVID-19 di Beijing memuncak, larangan masuknya warga asing ke Beijing diterapkan pemerintah pada 27 Maret.
Secara keseluruhan, angka kematian COVID-19 di Beijing lebih rendah dibandingkan epidemi SARS 2003 karena adanya upaya penanggulangan yang maksimal serta penegakan kebijakan yang agresif untuk menekan angka terinfeksi dan kematian akibat COVID-19. Selain itu, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting karena mampu mengurangi kontak langsung, misalnya mengurangi pemakaian uang tunai (cashless) serta memudahkan identifikasi terhadap status kesehatan, dan memudahkan distribusi informasi lewat Beijing Health Kit App yang digunakan oleh warga setiap hari. Adanya kontribusi sukarelawan juga penting karena mereka berperan membantu pendataan, pelayanan terhadap kebutuhan sehari-hari, dan berbagai aktivitas rumah lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang sedang dikarantina. Di samping beberapa upaya adaptasi untuk menekan angka kasus, penyebaran COVID-19 juga berdampak secara tidak langsung pada aspek politik negara Cina, yakni dengan meningkatnya tuntutan kebebasan untuk berpendapat, tepatnya setelah meninggalnya Dokter Li Wenliang (salah satu dari delapan dokter yang telah dibahas sebelumnya).
Pasca gelombang pertama, tanda-tanda normalisasi kehidupan publik yang sudah terlihat pada minggu pertama Juni tidak bertahan lama. Pada minggu kedua, kembali ditemukan tiga kasus, dua di antaranya berasal dari Pusat Peneliti Daging Hewan di Fengtai. Kemudian, pada 13 Juni, ditemukan enam kasus dari transmisi lokal di pasar grosir makanan terbesar di Asia, yakni Pasar Xinfadi di Kecamatan Fengtai. Merespon kasus tersebut, pemerintah dengan tanggap melakukan berbagai upaya. Pemerintah langsung melakukan tiga langkah penting: sweeping, testing, dan isolation. Testing semakin masif dilakukan pada gelombang kedua ini, di mana seminggu setelah kasus ini juru bicara pemerintah menyebutkan bahwa telah ada 2,3 juta penduduk yang dites. Di minggu kedua bulan Juni, pemerintah juga menerapkan standar pengelolaan dengan tingkat genting (mekanisme masa perang) dan pada minggu selanjutnya, ruang publik kembali ditutup. Sebagai upaya disipliner, pemerintah melakukan pemecatan terhadap beberapa pejabat dan pengelola pasar Xinfadi yang dianggap bertanggung jawab. Perbedaan gelombang kedua dan gelombang pertama secara signifikan terlihat lewat testing yang dilakukan dengan lebih masif dan agresif ke orang-orang yang terdampak langsung maupun tidak langsung, adanya peningkatan masa karantina dari 14 menjadi 21 hari, pendataan orang-orang yang semakin ketat, isolasi yang lebih bersifat lokal serta penanganan berbeda bagi tiap tingkatan dari high risk, moderate risk, hingga low risk.
Pemaparan kedua dilanjutkan oleh Arrizal dengan judul “Dari Beijing ke Jalanan Hong Kong: Bagaimana Mahasiswa Membentuk Gerakan Demokrasi di Cina Kontemporer”. Meski di tengah pandemi, masyarakat Hong Kong tetap melakukan peringatan terhadap tragedi Tiananmen 1989 pada tanggal 4 Juni lalu. Di Cina, Protes Tiananmen telah menjadi simbol resiliensi gerakan demokrasi. Meski demokrasi dianggap tabu dalam pemerintahan Cina, demokrasi telah lama menjadi bagian dari diskursus identitas nasional Cina. Sebelum akhirnya Perang Saudara Cina dimenangkan oleh Partai Komunis Cina (PKC) pada tahun 1949, para pemimpin saat itu berusaha mengadopsi demokrasi sebagai salah satu prinsip negara.
Protes—utamanya yang dimotori mahasiswa—di Cina telah terjadi sejak lama, namun tidak selalu dilakukan untuk melawan otoritas yang ada. Terdapat dua fase protes di dataran Cina, yaitu yang didukung oleh elit politik (era Mao tahun 1949-1976 hingga tahun 1989-sekarang) dan yang melawan elit politik (era Republik tahun 1911-1949 hingga awal pasca Mao tahun 1976-1989). Namun, protes-protes ini berkesinambungan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan.
Di bawah Deng Xiaoping, sistem politik Cina mengalami masa transisi dan tidak lagi menitikberatkan kebijakan pada aspek ideologi, sehingga mendukung adanya reformasi dalam ranah politik. Tidak seperti pada era Mao, PKC pada masa pemerintahan Deng Xiaoping mendorong publik untuk mengekspresikan opininya. Periode ini kerap disebut Beijing Spring (mengacu pada Arab Spring) karena memberi celah bagi gerakan prodemokrasi untuk muncul. Salah satu simbol yang paling berpengaruh adalah Tembok Xidan yang digunakan sebagai wujud “keterbukaan” PKC untuk melakukan agenda rejuvenasi.
Salah satu protes mahasiswa yang paling berpengaruh dalam sejarah Cina modern yang dimotori oleh kalangan mahasiswa adalah May Fourth pada tahun 1919. Protes ini diinisiasi untuk melawan hasil perjanjian Versailles yang dinilai “menjual” Cina pada negara-negara Barat dan Jepang. Peristiwa May Fourth kemudian menjadi tonggak gerakan mahasiswa di Cina dan mendorong gerakan nasionalisme di Cina. Pada tahun 1986, mahasiswa dari berbagai wilayah di Cina melaksanakan protes yang menuntut adanya reformasi politik. Protes ini pun mendapat dukungan tidak langsung dari Hu Yaobang, sekretaris jenderal PKC. Tiga tahun kemudian, terjadi protes Tiananmen untuk memperingati wafatnya Hu Yaobang. Peristiwa Tiananmen menjadi puncak dan hasil akumulasi dari protes-protes kecil mahasiswa sejak tahun 1976.
Menurut pemaparan Arrizal, terdapat setidaknya enam alasan mengapa protes dimotori oleh mahasiswa. Pertama, keberadaan kultur protes sejak masa pergerakan nasional yang kerap mendorong gerakan reformasi yang berasal dari universitas-universitas yang didirikan pada masa reformasi tersebut. Kedua, adanya dorongan moral dan identitas eksklusif mahasiswa karena mahasiswa dipandang sebagai kelompok yang memiliki privilese. Ketiga, lokasi yang terpusat; pada tahun 1930, 60% mahasiswa Cina terpusat hanya di dua kota, yaitu Beijing dan Shanghai. Keempat, sifat mahasiswa sebagai kelompok masyarakat sipil yang cukup otonom dibandingkan kelompok masyarakat sipil lainnya yang dibungkam. Kelima, keiistimewaan mahasiswa sebagai kelompok pertama yang terpapar ide mengenai demokrasi lewat pembelajaran di bangku kuliah dan diseminasi dari Barat. Terakhir, lemahnya keterikatan antara mahasiswa dan negara sejak imperial civil examination dihapus tahun 1905.
Untuk menutup pemaparannya, Arrizal menyampaikan bahwa protes mahasiswa yang terjadi sejak May Fourth tahun 1919, protes Tiananmen tahun 1989, hingga protes di Hong Kong saat ini tidak dapat dipandang sebagai gerakan yang sepenuhnya terpisah. Protes-protes tersebut merupakan satu kesatuan dari gerakan yang menuntut adanya demokrasi sejak awal. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Cina yang kini berbeda pun turut memengaruhi keberadaan protes serupa di abad ke-21.
Penulis: Denise Michelle
Editor: Medisita Febrina

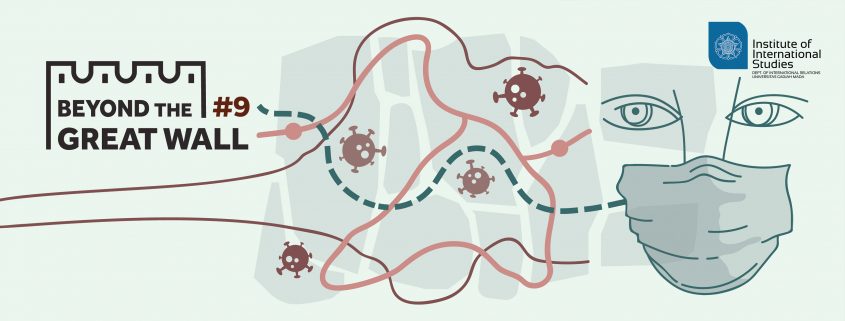
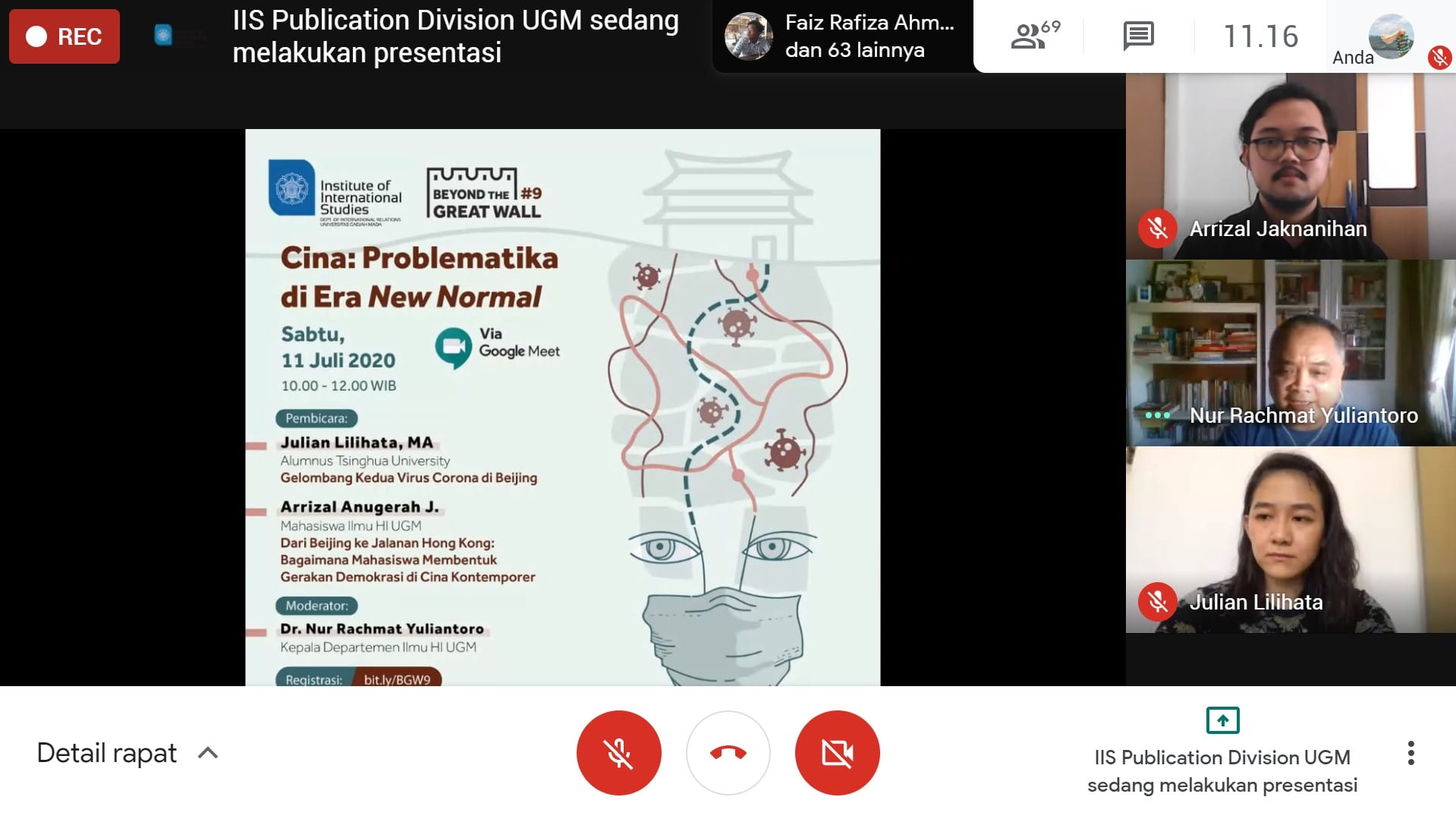
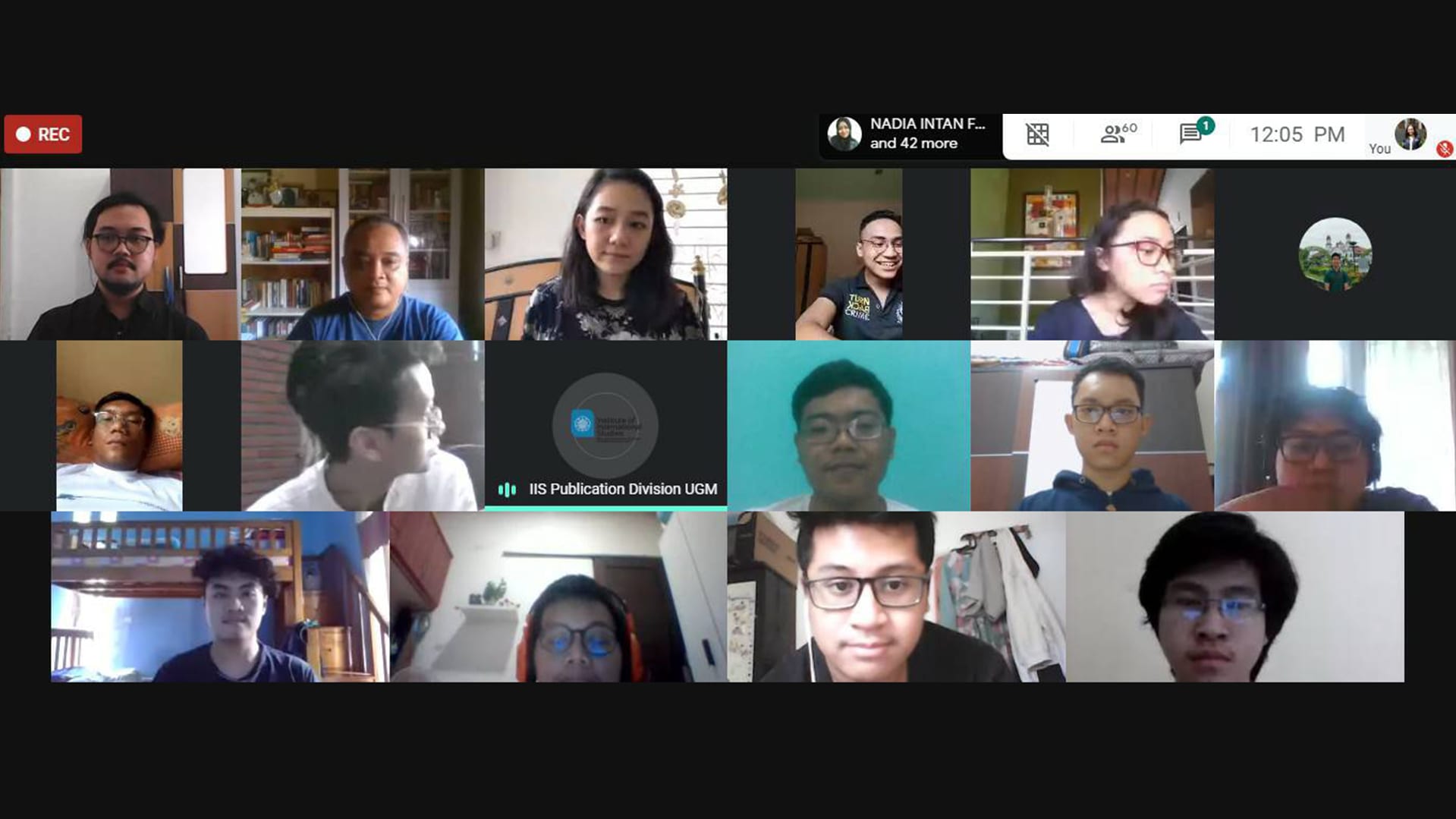


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!